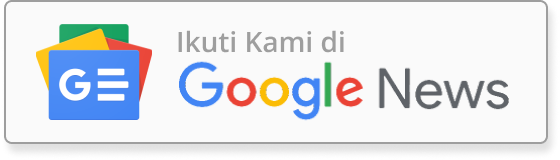Bioprospeksi berasal dari kata biodiversity prospecting. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia daring, belum kita dapati hasil kata bioprospeksi. Tak heran banyak pihak belum memahaminya. Mengutip sebuah sumber, bioprospeksi adalah upaya mengambil manfaat sosial-ekonomi sebesar-besarnya dari sumber-sumber biologis baru melalui koleksi, penelitian, dan pemanfaatan sumber daya genetik dan biologi secara sistematis, yang mengarah pada sumber-sumber baru senyawa kimia, informasi genetik, organisme dan produk alamiah lain untuk tujuan ilmiah atau komersial.
Bioprospeksi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) disebut bioekonomi yang sebenarnya merupakan gelombang ekonomi lanjutan dari masa natural economy pada 1900-an dan fossil economy pada 2000-an. Berlanjut di era pembangunan berkelanjutan sejak 2012, terjadi peleburan pendekatan dan strategi politik, ekonomi, lingkungan, dan keanekaragaman hayati dengan pembangunan dan industri yang kemudian berevolusi menjadi keberlanjutan pembiayaan bagi peningkatan nilai keanekaragaman hayati dan kompensasi jasa ekosistem untuk mencapai siklus kehidupan berkesinambungan.
Dalam perspektif pembangunan global, begitu pentingnya urusan dan hajat bioekonomi ini hingga pemerintahan negara berkumpul dalam konferensi tingkat tinggi Global Bioeconomy Summit (GBS). Diprakarsai oleh Dewan Bioekonomi Pemerintah Federal Jerman pada 2015, GBS mendiskusikan peluang dan tantangan serta mengembangkan visi bioekonomi berkelanjutan di masa depan di antara para aktor utama dari pemerintah, sains-inovasi, bisnis dan masyarakat sipil.
GBS ini kemudian menghubungkan kebijakan bioekonomi dengan pembangunan berkelanjutan dan agenda iklim global. Dari situ kita bisa memahami betapa pentingnya mengenal bioprospeksi lebih jauh dan manfaat yang dapat disumbangkan bagi perekonomian nasional dan global.
Bioprospeksi dari masa ke masa
Sejarah bioprospeksi paling monumental di Indonesia diawali terbitnya buku Herbariaum Amboinense karya botanis berkebangsaan Jerman G.E. Rumphius yang terbit 1743, memuat potensi rempah-rempah Maluku. Buku itu diterbitkan ulang pada 2003 dalam jurnal ethnopharmacology berjudul Bioprospecting Rumphius Ambonese Herbal, Volume 1. Sejarah kemudian mencatat kedatangan bangsa Eropa bersama kapal dagangnya berburu dan menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara.
Dalam perkembangannya, bioprospeksi kemudian dibicarakan secara global karena memiliki nilai pengetahuan strategis untuk pengembangannya dalam ekonomi pasar. Dalam konteks bioprospeksi, ada hubungan erat antara kepemilikan materi genetik, pengetahuan pemanfaatan dan teknologi pengembangannya serta mekanisme pembagian manfaat. Materi genetik yang memiliki potensi ekonomi tertentu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 yang merupakan ratifikasi dari Convention on Biological Diversity. Sementara perlindungan terhadap keamanan hayati produk rekayasa genetik telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang ratifikasi Protokol Nagoya diteken pemerintah untuk perlindungan dan peningkatan kapasitas dari custodian atau masyarakat ‘pemilik’ pengetahuan dan sumberdaya genetik, untuk tujuan membangun hubungan yang lebih setara antara masyarakat/custodian dengan industri dan akademisi/peneliti.
Definisi bioprospeksi mengutip kebijakan P.02/MenLHK/Setjen/Kum.1/1201 adalah kegiatan eskplorasi, ekstraksi, dan penapisan sumberdayaa alam hayati untuk pemanfaatankan secara komersil bailk dari sumberdaya genetik, spesies dan atau biokimian beserta turunannya. Sementara definisi teknis dari Pusat Inovasi LIPI, 2004 (sekarang BRIN) adalah penelusuran sistematik, klasifikasi, dan investigasi untuk tujuan komersial dari sumber senyawa kimia baru, gen, protein, mikroorganisme, dan produk lain dengan nilai ekonomi aktual dan potensial yang ditemukan dalam keanekaragaman hayati.
Keekonomian sumber daya genetik dalam bioprospeksi sangat menjanjikan. Mengutip begawan bioprospeksi Indonesia, Prof. Endang Sukara, tumbuhan rotan jernang besar (Calamus draco) di belantara hutan Sumatera yang digunakan suku Anak Dalam dan Talang Mamak sebagai pewarna alami ternyata mengandung senyawa dracorhodin. Penelitian di Cina pada 2017 mengungkap senyawa dracodhodin dapat mengatur proliferasi fibroblast yang berkaitan proses penyembuhan luka, dihargai senilai USD 12,9 per milligram atau lebih dari Rp 100 miliar per kilogram (Kehati, 2020).
Industri obat herbal dan jamu sudah lebih dulu memanfaatkan peluang ini dan mendapat pasar luas. PT Sido Muncul salah satu perusahaan jamu membukukan keuntungan sebesar Rp 2,6 triliun pada 2022, dengan peluang perluasan pasar ke negara-negara Afrika Timur (Kontan, 2023).
Selanjutnya:
Menilik Bioprospeksi dalam IBSAP pasca 2020 dan RPJPN 2025-2045