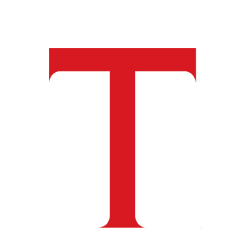Editorial Tempo.co
-----------
USULAN pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi yang datang dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri hanyalah ujung dari pelemahan lembaga anti-rasuah yang berlangsung secara sistematis. Meski kondisi KPK saat ini tidak seefektif dulu dalam memberantas korupsi, mandulnya KPK justru terjadi akibat ulah para elite partai politik sendiri.
Selama bertahun-tahun mereka berusaha mengacak-acak KPK di segala lini agar lembaga anti-rasuah menjadi tak bergigi. Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket oleh DPR, dengan dalih komisi ini sudah melanggar undang-undang, hanyalah salah satu siasat membungkam KPK yang saat itu tengah menyidik korupsi E-KTP. Pembentukan Pansus hanyalah akal-akalan Dewan demi melanggengkan praktik korupsi.
Upaya pelemahan mencapai puncaknya ketika pemerintah bersama DPR merevisi Undang-Undang KPK pada 2019. Sejak saat itu, posisi KPK berada dalam rumpun eksekutif, yang artinya di bawah presiden. Status pegawai KPK dipaksa menjadi aparatur sipil negara.
Pelemahan terhadap KPK makin menjadi-jadi. Di bawah kepemimpinan Firli Bahuri, KPK bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Badan Kepegawaian Negara menggelar tes wawasan kebangsaan. Seleksi ini terbukti hanyalah kedok untuk menyingkirkan para pegawai komisi antikorupsi yang kritis, termasuk penyidik senior yang banyak mengungkap kasus besar. Lewat tes yang serampangan, 57 pegawai berintegritas disingkirkan dari KPK.
Manuver KPK dalam memberantas korupsi juga diperumit. Ketika hendak menyadap, menggeledah, atau menyita, komisi antikorupsi wajib mendapat izin tertulis dari Dewan Pengawas, lembaga yang terbentuk lewat revisi UU KPK. Kehadiran Dewan Pengawas juga bagian dari skenario pelemahan ini.
Hampir bersamaan dengan revisi UU, DPR memilih lima pimpinan KPK periode 2019-2023 dari 10 nama usulan Presiden Joko Widodo yang diragukan integritasnya. Setelah terpilih, satu persatu pimpinan lembaga ini tersangkut pelanggaran etika.
Ketua KPK Firli Bahuri, misalnya, terbukti melanggar etik karena menerima pemberian fasilitas helikopter saat pulang kampung ke Batu Raja, Sumatera Selatan pada Juni 2020. Bau amis mengemuka karena diduga ada gratifikasi di balik penyewaan heli tersebut. Sayangnya, perkara ini tak berlanjut ke proses hukum. Sebelumnya, Firli juga pernah terseret pelanggaran etik ketika menjabat Deputi Penindakan KPK pada 2018 karena bertemu pihak berpekara.
Setali tiga uang dengan Firli, Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar diduga menerima fasilitas tiket dan akomodasi menonton MotoGP di Mandalika, Nusa Tenggara Barat pada Maret 2022. Sebelum Dewan Pengawas KPK membacakan putusan, Lili mundur lebih dulu dari KPK. Dewan Pengawas lantas menutup perkara ini.
Pengganti Lili di posisi Wakil Ketua, Johanis Tanak, juga tersandung pelanggaran etik. Ia diduga berkomunikasi dengan pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Padahal KPK tengah mengusut perkara korupsi di kementerian tersebut. Selain urusan etika, sesuai undang-undang, pemimpin KPK yang berkomunikasi dengan pihak berperkara termasuk perbuatan pidana.
Buruk laku pimpinan KPK kian menegaskan bahwa lembaga antikorupsi sudah rusak luar-dalam. Wajar bila kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini semakin tergerus. Tapi bukan berarti kita harus membubarkan KPK, seperti usulan Megawati Soekarnopurti kepada Presiden Jokowi.
Maraknya kasus korupsi juga tidak lepas dari sistem politik dan pemerintahan yang meminggirkan keterbukaan dan transparansi. Biaya tinggi untuk menjadi calon anggota legislatif turut menyuburkan korupsi di kalangan partai politik. Orang-orang yang paling terdepan mengusulkan pembubaran KPK adalah mereka yang punya komitmen rendah dalam memerangi korupsi.
Yang perlu didorong saat ini adalah memperbaiki lembaga antirasuah agar bisa kembali bergigi. Salah satunya dengan merevisi kembali UU KPK saat ini. Masyarakat sipil perlu berkonsolidasi.
Setuju dengan ide pembubaran KPK sama saja dengan kelakuan elit yang ingin melanggengkan korupsi. Pembubaran KPK akan membuat korupsi makin menjadi-jadi.