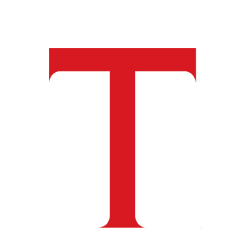Editorial Tempo.co
---
SISTEM penentuan penjabat kepala daerah belum berubah: cenderung ugal-ugalan dan tidak transparan. Prosesnya tertutup, mengabaikan masukan masyarakat, dan bertentangan dengan konstitusi. Praktik ini bukan hanya mencederai demokrasi, tapi juga mengancam kredibilitas hasil Pemilihan Umum 2024.
Awal September ini, 85 kepala daerah yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota berakhir masa jabatannya. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri, untuk penjabat gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi mengusulkan tiga nama ke Kementerian tersebut. Kementerian Dalam Negeri juga mengusulkan tiga kandidat. Tiga calon hasil penjaringan dari enam usulan itu nantinya dibawa ke Presiden Joko Widodo untuk dipilih satu nama.
Sedangkan untuk penjabat bupati atau wali kota, presiden juga menerima tiga usulan calon untuk dipilih menjadi satu nama. Tiga nama ittu hasil penjaringan sembilan kandidat yang diusulkan DPRD kabupatan atau kota, gubernur, dan Kementerian Dalam Negeri. Total tahun ini ada 170 kepala daerah yang berakhir masa jabatannya.
Kementerian Dalam Negeri tidak pernah mau membuka nama-nama kandidat penjabat kepala daerah sejak awal. Alasannya tak masuk akal: kontraproduktif hingga bisa menimbulkan konflik. Kementerian ini mengabaikan putusan Komisi Informasi (KI) nomor 007/I/KIP-PSI/2023 yang memenangkan gugatan lndonesia Corruption Watch yang meminta keterbukaan informasi soal penunjukan penjabat kepala daerah.
Putusan itu mewajibkan semua aturan hingga dokumen proses–sepanjang tak memuat data pribadi–bisa diakses publik. Dokumen penjaringan, usulan dan saran, pertimbangan dalam sidang tim penilai akhir (TPA), hingga rekam jejak calon penjabat kepala daerah merupakan informasi terbuka. Namun faktanya, masyarakat baru tahu nama-nama itu setelah mereka dilantik. Pendek kata, partisipasi publik dalam menentukan penjabat sementara itu selama ini nol besar.
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat pada 2016 sepakat menyatukan pemilihan kepala daerah dengan pemilihan presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat pada 2024. Wilayah yang periode pemimpinnya berakhir pada 2022 dan 2023 akan dipimpin penjabat kepala daerah. Sebanyak 271 kepala daerah berakhir masa jabatannya pada periode tersebut.
Dua putusan Mahkamah Konstitusi pada 2022 sudah memberi rambu tegas soal penentuan penjabat kepala daerah. Dua di antaranya adalah proses pemilihannya tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi serta perlu peraturan pelaksana untuk memastikan mekanisme yang akuntabel dan transparan.
Alih-alih membuat aturan pelaksana di bawah undang-undang, pemerintah justru merespons putusan MK itu dengan menerbitkan peraturan Menteri Dalam Negeri. Tindakan pemerintah ini merupakan perbuatan yang berlawanan dengan hukum karena bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Belakangan, Ombudsman RI menilai tindakan Mendagri membuat peraturan penjabat kepala daerah terbukti maladministrasi karena keliru menafsirkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Saat ini, setahun lebih setelah putusan Ombudsman, pemerintah tak kunjung menerbitkan peraturan pelaksana yang diminta MK agar penentuan penjabat kepala daerah dilakukan transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Tak heran kalau proses penentuan penjabat kepala daerah untuk 10 provinsi, 56 kabupaten, dan 19 kota yang akan berakhir pada September ini menuai sorotan. Misalnya beredar nama-nama kandidat dari polisi dan TNI aktif yang diusulkan DPRD ke Kementerian Dalam Negeri.
Pengisian penjabat kepala daerah dari kalangan TNI dan polisi aktif menabrak sejumlah aturan. Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, misalnya, menyebutkan jabatan tinggi pimpinan madya seperti kepala daerah diisi aparat sipil negara, bukan militer aktif. Tentara dan polisi duduk di kursi kekuasaan juga berbahaya bagi demokrasi. Tentara dan polisi semestinya tetap dijauhkan dari politik praktis.
Karut-marut penentuan penjabat kepala daerah ini wajar kalau menimbulkan syak wasangka. Sebab, mereka akan bertugas pada periode ketika Pemilihan Umum 2024 berlangsung. Tanpa aturan yang jelas dan prosesnya yang tak transparan, penentuan penjabat-penjabat sementara ini bisa dicurigai bermotif politik untuk pengamanan suara. Apalagi, tiga provinsi yang masa jabatan gubernurnya berakhir September 2023 merupakan lumbung suara, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Kepala daerah memiliki peran krusial dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Penjabat yang dipilih serampangan bisa memicu pemilu yang tak demokratis. Mereka bisa menggerakkan birokrasi di bawahnya untuk memenangkan calon tertentu.
Akibatnya, ketika terjadi gugatan hasil pemilihan presiden, sengketanya akan semakin rumit. Tuduhan-tuduhan kecurangan pemilu selama ini ini banyak diarahkan pada pelaksanaan pemungutan suara di level daerah. Fenomena ini terjadi pada sengketa hasil pemilihan presiden 2019 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Dengan tidak transparannya penentuan penjabat kepala daerah, tuduhan akan kecurangan pemilu boleh jadi semakin masif.
Penentuan penjabat kepala daerah tanpa melibatkan masyarakat juga mencederai demokrasi. Posisi yang diisi para penjabat tersebut merupakan jabatan publik, yang pergantiannya melalui mekanisme pemilihan oleh rakyat. Karena mereka inilah nantinya yang akan memerintah selama belum terpilihnya kepala daerah definitif.
Pemilihan penjabat kepala daerah yang tidak memperhatikan aspirasi dan melibatkan masyarakat sama artinya pembajakan hak mereka untuk memilih pemimpinnya.