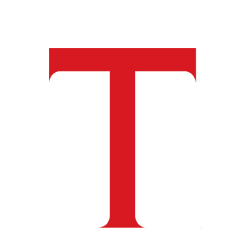Editorial Tempo.co
-----------------
Dua laporan di penghujung Juni lalu, masing-masing dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dana Moneter Internasional (IMF), semestinya sudah cukup menjadi alasan bagi Presiden Joko Widodo untuk segera mengevaluasi program hilirisasi industri pertambangan secara lebih komprehensif. Jika tidak, ambisi meningkatkan nilai tambah hasil tambang hanya akan membuahkan seabrek masalah ketimbang manfaat besar bagi perekonomian.
Masalah pertama bersumber dari jurus yang dipilih pemerintah untuk mendorong hilirisasi industri pertambangan: melarang ekspor mineral mentah. Kajian awal Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK mengungkap ekspor ilegal bijih nikel justru marak ketika Jokowi memberlakukan kebijakan tersebut pada 1 Januari 2020. Kantor bea dan cukai Cina mencatat importasi bijih nikel dari Indonesia sepanjang Januari 2020 hingga Juni 2022 sebanyak 5,3 juta ton. Nilai impor produk hasil pertambangan nikel yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik di periode yang sama juga lebih rendah Rp 14,5 triliun dibandingkan data otoritas Tiongkok.
Pemerintah semestinya belajar dari pengalaman sewindu lalu. Problem serupa pernah mencuat ketika pemerintah memberlakukan pembatasan ekspor mineral hasil tambang pada 2014. Angka volume ekspor bijih nikel 2015 dalam data BPS dan Kementerian Perdagangan berbalik arah, menjadi jauh lebih rendah dibandingkan versi otoritas negara-negara importir. Praktik ekspor ilegal ditengarai telah menggantikan modus pelaporan harga penjualan di bawah nilai transaksi sebenarnya (mark down) yang mewarnai perdagangan nikel satu dekade sebelumnya.
Ketimbang menutup keran ekspor yang memicu ekspor ilegal dan menggerus potensi pendapatan negara dari sektor pertambangan, pemerintah sebenarnya punya opsi lain untuk mendorong hilirisasi industri. Pemerintah bisa mengenakan tarif pajak tinggi, baik terhadap penghasilan eksportir maupun atas komoditas mineral mentah yang diperdagangkan. Selain dapat menambah penerimaan perpajakan, cara ini akan memudahkan pemerintah untuk mengendalikan kebijakannya hilirisasi sesuai dengan situasi pasar.
Namun program hilirisasi pertambangan sejak awal tak disiapkan secara cermat. Pemerintah hanya memikirkan cara menarik investasi sebesar-besarnya untuk meningkatkan kapasitas pabrik peleburan (smelter) yang akan mengolah nikel mentah. Asumsinya, tumbuhnya industri pengolahan akan menambah lapangan kerja sekaligus mendongkrak nilai perdagangan produk olahan hasil tambang. Kebijakan larangan ekspor nikel mentah dianggap sebagai cara paling ampuh untuk mewujudkan ambisi tersebut.
Sepintas, strategi pemerintah jitu. Melihat adanya jaminan pasokan bahan baku dari negara pemilik cadangan nikel terbesar di dunia, investor asing berdatangan membangun smelter. Jumlah pabrik pengolahan nikel meningkat menjadi 20 smelter dari hanya tiga unit pada 2014. Nilai ekspor produk olahan nikel, feronikel, dan baja tahan karat tahun lalu mencapai US$ 33,81 miliar, melonjak sepuluh kali lipat dibandingkan sebelumnya hilirisasi yang rata-rata per tahun hanya US$ 3 miliar. Pemerintah hakulyakin angkanya akan terus bertambah seiring rencana tambahan 30 smelter baru yang sedang mengantre dibangun.
Namun benarkah ekonomi telah mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari program hilirisasi ala pemerintah? Pertanyaan besar ini yang sebenarnya hendak disampaikan IMF dalam laporan hasil konsultasi tahunan dengan Indonesia yang dirilis 25 Juni lalu. IMF mendukung ambisi pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah ekspor nikel dan menarik investasi asing. Namun lembaga keuangan internasional itu menilai program hilirisasi perlu diperjelas dengan analisis beban dan manfaat. Mereka berharap pemerintah mempertimbangkan untuk mengakhiri larangan ekspor nikel mentah dan tak menerapkan kebijakan serupa pada komoditas mineral lain.
Kuping pemerintah tak perlu panas mendengar saran tersebut. Ketimbang memaki, seperti Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang merasa IMF mencampuri kedaulatan negara, pemerintah memang semestinya mengidentifikasi beban yang ditimbulkan oleh desain hilirisasi sekarang ini. Dengan begitu, program hilirisasi hasil tambang benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi ekonomi.
Maraknya ekspor ilegal bijih nikel selama tiga tahun merupakan salah satu beban dalam implementasi hilirisasi hasil tambang yang hanya bertumpu pada kebijakan larangan ekspor. Pemerintah perlu menindak tegas praktik lancung yang merugikan negara tersebut. Namun di sisi lain, pemerintah harus membenahi faktor lain yang menjadi pemicunya: rusaknya struktur industri akibat posisi dominan investor smelter di sektor hulu pertambangan.
Larangan ekspor nikel mentah menempatan pabrik peleburan sebagai negara dalam negara. Merekalah yang menentukan produk mineral mentah siapa dan dengan kualitas seperti apa yang dapat diolah sehingga bisa diekspor. Menghadapi dominasi pengusaha smelter, pengusaha tambang hanya punya dua pilihan agar bisnisnya berlanjut: bekerja sama atau menyelundupkan produknya lewat pasar gelap. Masalahnya, dua opsi itu juga tak gratis, perlu ongkos tambahan untuk mendapatkan “pelindungan” dari orang-orang kuat di Jakarta. Itu sebabnya banyak politikus, aparat, hingga pejabat pemerintahan yang bercokol di sejumlah perusahaan. Tanpa aturan yang jelas, kebijakan hilirisasi rentan menjadi ladang korupsi yang hanya menguntungkan para pencari rente.
Beban lain yang belum pernah diukur pemerintah, setidaknya karena tak pernah dibuka kepada publik, adalah dampak negatif dari pembangunan smelter-smelter raksasa terhadap masyarakat dan lingkungan. Konflik agraria disertai pelanggaran hak asasi manusia meletus di sejumlah daerah yang disulap menjadi kawasan industri pengolahan nikel. Sedangkan angka deforestasi dalam tren menanjak seiring bertambahnya lubang tambang tiga tahun terakhir di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, dan Maluku Utara yang kaya nikel.
Di tengah tak jelasnya ujung dari rencana hilirisasi yang disusun pemerintah, semua persoalan tersebut bisa menumpuk hingga menjadi tanggungan biaya amat besar yang harus ditanggung negara di masa mendatang. Pemerintah sebaiknya menghitung ulang kebijakannya secara menyeluruh dan membuka hasilnya kepada publik. Hanya dengan begitu, kita bisa percaya bahwa kebijakan itu dibuat tidak untuk memperkaya segelintir pebisnis yang dekat dengan penguasa.