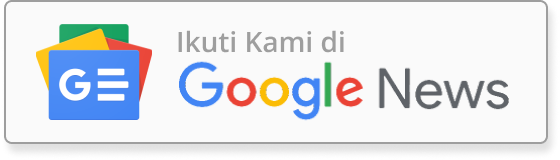Pembangunan infrastruktur tampaknya tetap menjadi andalan pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi pada tahun 2021. Salah satu targetnya adalah pada penguatan infrastuktur digital di sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya.
Namun, kendala keterbatasan kapasitas fiskal membuat pemerintah harus memutar otak menemukan jurus-jurus alternatif, misalnya melalui pelibatan swasta dalam skenario Public Private Partnership (PPP), jika tidak ingin serta merta menempuh jalur pembiayaan hutang.
Tulisan ini mencoba melihat skema alternatif dalam pembangunan infrastruktur, dengan mengambil contoh penggunaan bersama sarana digital antara industri ekstraktif dengan masyarakat pedesaan untuk mendukung sektor pendidikan, sekaligus menjadi titik tolak agenda reformasi tata kelola sumberdaya nasional.
Secara agregat, Indonesia sebenarnya termasuk pengguna teknologi tertinggi di bidang pendidikan di dunia. Cambridge International pada tahun 2018 merilis bahwa siswa Indonesia terbanyak menggunakan ruang IT/komputer (40%) di sekolah, dan kedua tertinggi dalam penggunaan komputer desktop (54%), setelah Amerika Serikat.
Akan tetapi tekanan di sektor pendidikan meningkat drastis karena protokol kesehatan mengharamkan pembelajaran tatap muka selama masa pandemi. Pembelajaran daring menuntut ketersediaan sarana digital yang memadai.
Sementara itu hanya sekitar 40% guru yang siap dengan teknologi. Kondisi ini diperparah dengan kekurangan smartphone dan keterbatasan jaringan internet di daerah-daerah terpencil atau pedesaan.
Jika keadaan ini terus berlanjut maka Indonesia dapat mengalami kehilangan generasi (lost generation), atau minimal lonjakan ketimpangan pendidikan kota-desa.
Sekarang saatnya kita menimbang strategi shared-use or open access infrastruktur sektor ekstraktif sebagai salah satu alternatif penyediaan infrastruktur publik.
Penggunaan Bersama atau Shared Use
Operasi tambang dan industri ekstraktif lainnya seperti migas dan perkebunan, selalu membutuhkan infrastruktur untuk mengembangkan sistem bisnis dan operasional yang rumit di wilayah kerjanya. Jika beroperasi di daerah terpencil dan tertinggal, perusahaan harus mengembangkan sarana sendiri sebagai bagian dari investasi.
Karena itu, kantor-kantor lapangan biasanya dilengkapi dengan jaringan internet yang cepat dan tidak terbatas, di mana penggunaannya sering menjadi hak eksklusif perusahaan tersebut.
Shared-use adalah gagasan penggunaan infrakstruktur perusahaan secara bersama-sama dengan masyarakat sekitar. Salah satu fasilitas yang dapat menjadi sasaran penggunaan bersama ini adalah jaringan internet.
Dalam suasana krisis seperti sekarang ini, tidak ada alasan lagi bagi korporasi untuk terus menjustifikasi penggunaan eksklusif yang sudah terlalu lazim itu.
Jaringan internet perusahaan harus bisa diperluas hingga ke desa-desa sekitar tambang untuk mendukung infrastruktur digital. Koneksi internet niscaya akan membantu anak-anak untuk mengakses pendidikan dan mengirim tugas-tugas.
Perusahaan pertambangan, migas, dan perkebunan juga dapat membuka kantor atau bangunan-bangunan lain mereka untuk para guru dan sekolah desa yang tidak memiliki internet, misalnya untuk mengakses materi pengajaran, atau setidaknya mengakselerasi kapasitas tenaga pendidik.
Yang terpenting, skema ini tidak membutuhkan dana pemerintah maupun pembiayaan hutang. Negara juga tidak perlu meyakinkan swasta melalui studi kelayakan yang mahal dan panjang.
Dengan mengadopsi inisiatif ini, negara dapat memperoleh alternatif tambahan untuk menyediakan infrastruktur digital di desa-desa kaya sumberdaya namun selama ini masih relatif tertinggal secara multi aspek. Yang kita butuhkan hanyalah sense of crisis yang cukup, kemauan politik dari pemerintah, dan niat baik pelaku industri ekstraktif.
Meluruskan fungsi CSR dan program pemberdayaan masyarakat
Walaupun tidak ada nilai investasi secara spesifik, tetapi satu hal yang pasti bahwa biaya penggunaan bersama ini jauh lebih murah dibanding apabila pemerintah harus membangun infrastruktur digital sendiri.
Biaya yang sangat ekonomis ini dapat dengan mudah ditutup oleh program CSR atau Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Pada tahun 2019, belanja sosial perusahaan tidak kurang dari 3 trilyun rupiah hanya untuk sektor mineral dan batubara saja.
Banyak pihak selama ini salah kaprah dalam memahami tanggungjawab sosial perusahaan. CSR diidentikkan dengan kegiatan sosial perusahaan untuk masyarakat dan lingkungan hidup yang dianggap sebagai bagian dari alokasi keuntungan.
Oleh karena itu, kebanyakan industri memperlakukan program CSR sebagai kebijakan residu yaitu alokasi residu sisa keuntungan (laba) dan bukannya sebagai kebijakan strategis yang utama oleh industri.
CSR seolah-olah menjadi instrumen alat tukar menukar demi pencapaian sebuah tujuan kolonial yang dipoles secara lebih modern: memperoleh izin sosial untuk berusaha (social license to operate). Akibatnya, CSR dan agenda pengembangan masyarakat lainnya lebih banyak menyasar program-program pragmatis seperti berbagai macam bantuan sosial.
Sementara kalangan bahkan menganggap CSR hanya sebatas urusan bagi-bagi uang demi memuluskan operasi perusahaan, sehingga dana CSR lebih banyak dinikmati oleh para pemburu rente dan politisi oportunis.
Hal ini diperparah oleh sikap pemerintah sebagai regulator yang cenderung gagap dalam melihat perkembangan kontemporer.
Selama puluhan tahun, kementerian yang membidangi energi dan sumberdaya mineral terus menempatkan perusahaan sekedar sebagai agen penghasil revenue tanpa benar-benar sebagai mitra strategis yang dapat mengakselerasi kondisi sosial dan ekonomi desa.
Masyarakat pada daerah yang kaya sumberdaya tidak pernah benar-benar mandiri. Kedatangan investasi telah merenggut lahan-lahan yang selama ini menjadi aset penduduk. Dengan iming-iming pembukaan lapangan kerja dan segenap manfaat ekonomi lainnya, investasi pertambangan membalik keadaan dan membuat masyarakat menjadi tergantung terhadap aktivitas yang bersifat eksploitatif.
Data tahun 2018 misalnya sekitar 85% perekonomian Kabupaten Mimika bergantung semata-mata pada aktifitas tunggal pertambangan emas PT Freeport. Sementara itu lebih dari 65% perekonomian Kutai Kertanegara ditopang oleh sektor pertambangan dan migas.
Kolaka sebagai salah satu kabupaten penghasil nikel justru mengalami perkembangan buruk ketika hampir 50% perekonomiannya tergantung dari pertambangan. Padahal sekitar 15-20 tahun lalu angka ini hanya berkisar antara 8-15% saja.
Di sisi lain, penelitian Publish What You Pay Indonesia tahun 2017 menunjukkan bahwa kantong-kantong kemiskian banyak ditemukan di sekitar wilayah operasi industri ekstraktif di Sumbawa Barat, Indragiri Hulu dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Situasi ini tentu saja sangat riskan mengingat pertambangan adalah sumberdaya yang tidak terbarukan. Ketika perusahaan tambang tutup maka dampak buruk ketergantungan tersebut mulai kelihatan wujudnya. Masyarakat akan kehilangan mata pencaharian dan perekonomian lokal menjadi lumpuh akibat kehilangan penopang utamanya dalam sekejap.
Beban penduduk lokal akan semakin berlipat saat perusahaan meninggalkan kerusakan lingkungan yang membuat lahan-lahan menjadi tidak produktif untuk sektor-sektor lain seperti yang selama ini banyak terjadi.
Reformasi tata kelola sumberdaya
Perjalanan tata kelola industri ekstraktif selama ini telah jelas salah arah. Investasi pertambangan yang digadang-gadang dapat membantu perekonomian nasional justru telah menunjukkan gejala pertumbuhan semu.
Kedatangan modal malah menghilangkan kemandirian lokal, dan menempatkan masyarakat pada posisi yang sangat rentan terhadap setiap gejolak ekonomi dan tekanan harga komoditas global. Kejatuhan harga batubara dunia misalnya dapat membuat masyarakat sekitar pertambangan jatuh miskin seketika.
Pandemi harusnya sekaligus menjadi momentum untuk menata kembali tata kelola sumberdaya nasional. Sudah saatnya pelaku industri dan pemerintah keluar dari jebakan perspektif masa lalu.
Pendekatan primitif tersebut telah membuat investasi sektor ekstraktif bekerja mirip seperti narkoba: menciptakan ketergantungan sekaligus memberi efek candu (addictive) bagi masyarakat.
Hal ini misalnya tampak pada sebagian masyarakat Pulau Bangka dan Belitung yang tidak bisa lepas dari ketergantungan menambang timah.
Program-program pemberdayaan harus mampu membuat masyarakat lebih mandiri dan mendorong diversifikasi ekonomi. Sharing infrastruktur teknologi digital hanyalah salah satu cara agar industri eksktraktif dapat memberi daya ungkit sosial dan ekonomi masyarakat lokal.
Penggunaan bersama juga dapat menyasar infrastruktur yang lain. Dalam skala yang lebih luas, program ini harusnya dapat membantu masyarakat untuk mengakses lembaga keuangan (perbankan), logistik, dan pasar.
Dengan begitu, ekonomi pedesaan dapat tereksplorasi secara maksimal. Kebijakan ini pada dasarnya membuka potensi sosial dan ekonomi lokal yang selanjutnya dapat menghasilkan masyarakat pedesaan yang kompetitif.
Sharing infrastruktur bukan hanya memperkuat kerjasama dengan para pemangku kepentingan khususnya masyarakat dan pemerintah lokal. Dalam sudut pandang bisnis, program ini dapat memperkuat brand perusahaan, meningkatkan citra korporasi, dan memberi nilai lebih dibanding kompetitornya.
Strategi berbagi infrastruktur antara industri ekstraktif dengan masyarakat lokal merupakan perwujudan prinsip investasi yang bertanggungjawab sosial dengan tujuan akhir keberlanjutan (sustainability).
Lebih dari itu, kebijakan ini dapat dianggap sebagai kompensasi terhadap penerimaan masyarakat dan izin pemerintah atas pengembangan proyek-proyek industri ekstraktif.