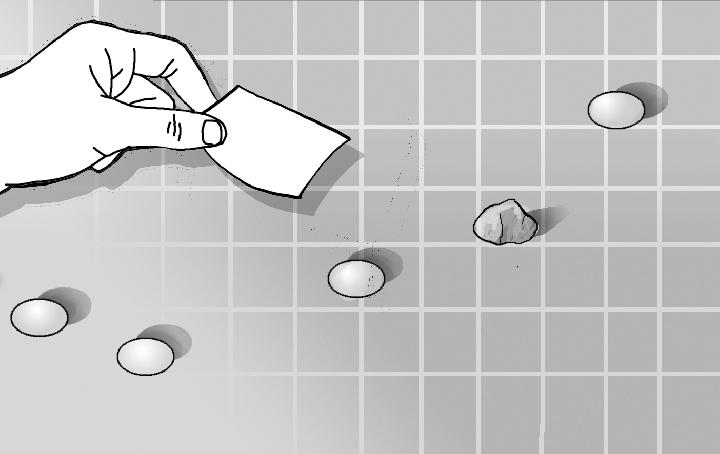Tulus Abadi
Ketua Pengurus Harian YLKI
Mengeluh dan mengadu merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki konsumen. Bahkan, secara kultural, hal tersebut sudah terjadi sejak era kerajaan Mataram, tepatnya di era Hamengku Buwono VIII (1900), saat masyarakat melakukan protes kepada raja dengan aksi tapa pepe (berjemur di depan keraton) untuk menuntut keadilan. Dalam konteks modern seperti sekarang, siapa pun tak boleh telinganya merah terhadap keluhan/pengaduan konsumen. Apalagi keluhan itu dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Untuk mewujudkan haknya, lazimnya konsumen tidak berjalan sendirian, melainkan memerlukan katalisator, misalnya melalui Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), yang telah menjadi katalisator sejak 1973.
Keluhan dan pengaduan konsumen mempunyai makna dan fungsi strategis bagi perlindungan konsumen secara keseluruhan. Keberanian konsumen untuk mengadu menjadi indikator paling kuat untuk menentukan tingkat indeks keberdayaan konsumen (IKK). Hasil survei oleh Kementerian Perdagangan (2019) yang bekerja sama dengan IPB menunjukkan bahwa skor IKK di Indonesia adalah 41,07, naik dari 40,41 pada 2018. Namun tingginya angka pengaduan konsumen juga mengindikasikan bahwa manajemen penanganan keluhan oleh operator/pelaku usaha dan bahkan pengawasan oleh regulator tidak efektif. Konsumen tak perlu bersusah-payah mengadu ke lembaga konsumen jika manajemen penanganannya berjalan optimal.
Tingginya jumlah keluhan dan pengaduan konsumen via Bidang Pengaduan YLKI pada 2019 juga menjadi bukti fenomena tersebut. Pada 2019, YLKI telah menerima 1.871 aduan, terdiri atas 563 kasus kategori individual dan 1.308 kasus kategori kelompok/kolektif. Sepuluh besar pengaduan konsumen individual (563 aduan) meliputi masalah perbankan (106 kasus), pinjaman online (96), perumahan (81), belanja online (34), leasing (32), transportasi (26), kelistrikan (24), telekomunikasi (23), asuransi (21), dan pelayanan publik (15).
Dari sepuluh jenis aduan itu, pengaduan konsumen atas produk jasa finansial sangat dominan (46,9 persen) yang meliputi lima komoditas, yakni bank, uang elektronik, asuransi, leasing, dan pinjaman online. Peringkat berikutnya diduduki oleh sektor perumahan (14,4 persen), e-commerce (6,3), ketenagalistrikan (4,2), dan telekomunikasi (4,1).
Yang paling memprihatinkan adalah pengaduan konsumen soal pinjaman online, dengan korban mayoritas masyarakat kecil/miskin. Bahkan dampak dari masalah ini telah memakan korban jiwa (bunuh diri), perceraian, dan pemecatan oleh perusahaannya. Konsumen terjerat masalah ini umumnya dari cara penagihan juru tagih yang meneror konsumen atau mempermalukannya di mata saudara, teman dekat, atasan, dan kolega di kantor.
Menurut catatan YLKI, mayoritas pelaku usaha pinjaman online yang diadukan adalah pelaku usaha ilegal (54 pelaku). Namun ada juga 17 pelaku usaha yang legal atau terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Walau OJK mengklaim telah memblokir pengusaha ilegal, buktinya korbannya masih cukup marak. Tragisnya, korban adalah masyarakat menengah ke bawah (orang miskin) yang terjerat bunga berbunga yang sangat tinggi dan denda harian yang mencekik leher, sehingga konsumen harus membayar lebih dari 100 persen utang pokoknya.
Masih tingginya jumlah pengaduan di bidang jasa keuangan ini mengindikasikan ada suatu permasalahan yang serius, khususnya pengawasan oleh regulator. Jika disandingkan dengan pengaduan konsumen di negara lain, seperti Singapura atau Hong Kong, hal tersebut tidak terjadi lagi. Selama 2017-2019, pengaduan konsumen jasa keuangan di lembaga konsumen di Hong Kong menduduki peringkat ke-15. Di Indonesia, sejak 2012 sampai 2019, pengaduan masalah keuangan menduduki peringkat pertama. Belum lagi jika bicara kasus asuransi yang melilit PT Jiwasraya atau perusahaan asuransi lain, yang pengaduannya di YLKI juga dominan, maka dengan gamblang kinerja pengawasan OJK tampak sangat kedodoran.
Dominannya pengaduan atas produk jasa finansial tersebut memiliki benang merah sebagai berikut. Pertama, literasi finansial konsumen masih rendah sehingga tidak memahami secara detail apa yang diperjanjikan dalam produk jasa tersebut. Kedua, minimnya edukasi dan pemberdayaan konsumen yang dilakukan operator. Operator hanya piawai memasarkan produk tapi malas memberikan edukasi dan pemberdayaan kepada konsumennya. Ketiga, pengawasan yang lemah oleh regulator, khususnya OJK. YLKI menduga masih lemahnya pengawasan OJK ini karena OJK tidak punya kemerdekaan finansial dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Saran konkret untuk mengatasinya adalah reformasi atau bahkan transformasi di lingkup internal dan institusional OJK. Tidak hanya meningkatkan pengawasannya, tapi juga persoalan hulu di OJK. Misalnya, soal iuran industri finansial kepada OJK untuk biaya operasional OJK. Ini sebenarnya paradoksal: bagaimana OJK akan mengawasi kinerja industri finansial tapi 100 persen biaya hidupnya dari mereka? Perubahan hal tersebut sangatlah mendesak sehingga biaya operasional OJK sepenuhnya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tanpa reformasi dan transformasi semacam itu, kinerja OJK dalam pengawasan dan perlindungan konsumen akan tetap kedodoran, bahkan mandul.