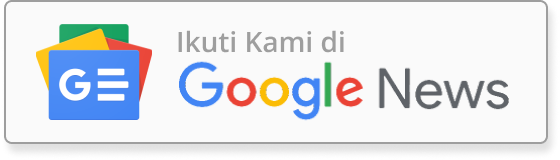Wasisto Raharjo Jati
Peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI
Panggung politik digital di dunia maya Indonesia selama 2018 semakin menunjukkan adanya eskalasi narasi intoleransi yang semakin menguat. Kondisi ini sebenarnya mirip dengan situasi pada 2017 saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta berlangsung dan media sosial menjadi ajang pertempuran. Hanya, kini pertempuran tersebut tidak lagi menyoal teologi-ukhrawi, tapi lebih pada perebutan materi. Hal tersebut terindikasi dari maraknya sikap bias melihat dan mencampuradukkan agama dan politik dalam panggung kampanye pemilihan presiden 2019.
Di satu sisi, amalgamasi agama dan politik di ranah dunia maya telah mengaburkan rasionalitas, yang berujung pada pemujaan figur. Di sisi lain, amalgamasi politik dan agama tersebut justru berujung pada sikap irasionalitas dalam membaca realitas. Gambaran seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia dimabukkan dengan masalah identitas tapi alpa merawat rasionalitas.
Gejala militansi terhadap agama bukan tanpa sebab. Hal ini akibat minimnya keinginan masyarakat untuk saling bernegosiasi dan peduli terhadap perbedaan. Akibatnya, terjadi benturan kepentingan satu sama lain, yang pada akhirnya menjadikan isu politik sebagai senjata. Agama menjadi senjata yang sekarang tren, dan ini bisa dilihat dari upaya untuk membentengi diri dari kalangan konservatif serta upaya menaikkan diri sebagai kalangan mayoritas. Dalam berbagai sudut pandang, keduanya bertaut, yang pada akhirnya esensinya sama: siapa yang paling lama duduk di tampuk kekuasaan.
Masyarakat Indonesia pada dasarnya sadar politik tapi awam informasi politik. Kondisi ini dimaksimalkan dengan semakin merebaknya fitnah, ujaran kebencian, dan berita bohong di ruang publik. Masyarakat menjadi korban propaganda, yang menjadikan mereka alat untuk meraih kekuasaan elite.
Sebenarnya, praktik politik digital di arena media sosial warganet Indonesia awalnya berlangsung secara dinamis pada 2017. Namun hal tersebut berubah ketika kepentingan politik mulai menyusupi arena diskusi netizen. Hal yang pada mulanya masalah pribadi ditarik menjadi soal teologi. Hal yang dasarnya soal pemenuhan materi ditarik ke urusan politik. Uniknya lagi, labelisasi sosial kemudian berlaku dalam percakapan di media sosial antara pendukung A dan pendukung B. Keributan itu hampir menjadi menu tiap hari yang berujung pada aksi-aksi kekerasan verbal dan nonverbal.
Dalam konteks ini, kita melihat bahwa euforia kebebasan masyarakat Indonesia terhadap peranti digital semakin lama semakin terdistorsi. Hal yang semula sebagai ajang eksistensi dan artikulasi, kini berkembang menjadi ajang filterisasi sosial. Akal sehat tidak lagi digunakan karena sudah terdogma dengan berita dan informasi tidak akurat sehingga menciptakan penggiringan opini, entah itu baik ataupun positif.
Masyarakat sangat gemar terpengaruh narasi ketertindasan mayoritas, yang sebenarnya masih menunjukkan mental intoleran. Hal itu bisa saja memicu eksklusivitas sosial di kalangan masyarakat lain, yang membuat tidak adanya jalinan negosiasi di antara sesama orang Indonesia. Padahal, sejatinya, negosiasi itu menjadi akar masyarakat Indonesia, yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Spirit tersebut telah berganti dengan semakin intensnya penyempitan perspektif masalah pada aksi tagar. Munculnya tagar tidak berarti memberikan solusi baru, tapi malah menciptakan kompetisi. Pada akhirnya, mekanisme musyawarah untuk menghasilkan konsensus sekarang semakin dimaknai menjadi ajang pengumpulan massa terbanyak sebagai nilai kebenaran.
Apalagi kini menggejala isu politik identitas. Sebenarnya, politik identitas itu muncul kalau ada ketertindasan yang dirasakan kalangan minoritas. Namun, dalam konteks Indonesia, justru yang mayoritas merasa menjadi minoritas dan ingin memainkan isu ketertindasan. Pemutarbalikan posisi dan fakta ini jelas mengandung kepentingan politik. Ironisnya, aktor-aktor mayoritas bermental minoritas itu abai terhadap dampak jangka panjang dan menghamba pada kekuasaan yang semu. Ujungnya jelas: isu akan digoreng dan mobilisasi massa.
Menjelang pemilihan presiden, mengedepankan sikap waras, baik pikiran maupun hati, menjadi mutlak. Terlebih lagi para elite, yang kerap menjadikan masyarakat semakin terpolarisasi. Salah satu cara menangkal amalgamasi agama dan politik adalah mengedepankan kampanye programatik, yang dipertarungkan adalah program dan gagasan, bukan sindiran berbasis identitas. Kandidat harus memulai langkah ini dengan menanggalkan identitasnya sebagai politikus yang ideolog, bukan yang demagog, yang senantiasa memainkan isu penistaan dan ketertindasan untuk meraih suara.