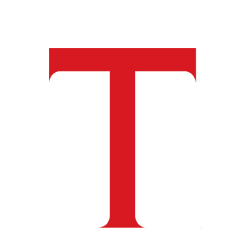PEMERINTAH dan Dewan Perwakilan Rakyat harus menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang rencananya dilakukan pada pertengahan bulan ini. Sarat dengan pasal bermasalah, rancangan kitab undang-undang tersebut prematur untuk dijadikan undang-undang.
Sejumlah pasal dalam rancangan itu bahkan lebih buruk dibanding KUHP saat ini-warisan kolonial Belanda yang berusia lebih dari satu abad. Sebagian di antaranya berpotensi mengancam kehidupan demokrasi di negara ini. Misalnya, pemberlakuan kembali pasal penghinaan presiden, yang dulunya diadopsi dari pasal penghinaan terhadap raja atau ratu Belanda. Padahal, Mahkamah Konstitusi sudah menghapus pasal karet itu pada 2006 karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dianggap tak lagi relevan. Delik itu juga menegasikan kesetaraan semua warga negara di hadapan hukum.
Pemerintah dan DPR pun kembali membangkitkan pasal penghinaan terhadap pemerintah yang sudah dikubur Mahkamah Konstitusi pada 2007. Rancangan KUHP juga menambahkan pasal penghinaan terhadap pengadilan, yang salah satunya menyangkut integritas hakim. Semua pasal itu jelas mengancam kebebasan berpendapat. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, banyak pengkritik pemerintah yang diadukan ke kepolisian dan diseret ke pengadilan. Bukannya membenahi kondisi itu, lewat rancangan ini, pemerintah dan DPR malah memberi payung hukum bagi tindakan represif. Publik kelak tak lagi bisa dengan bebas menyampaikan pendapat dan kritik karena dapat terkena hukuman pidana.
Tajam kepada mereka yang kritis, pisau Rancangan KUHP justru tumpul terhadap koruptor. Sebagian pasalnya nyata-nyata melemahkan pemberantasan korupsi. Pemerintah dan DPR bersepakat meringankan hukuman bagi koruptor, yaitu minimal 2 tahun bui. Padahal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa para penggangsir duit negara dihukum minimal 4 tahun kurungan. Begitu pula dengan tindak pidana pencucian uang. Rancangan KUHP menyebutkan hukuman maksimal 15 tahun kurungan dan denda Rp 5 miliar untuk kejahatan tersebut, jauh lebih ringan ketimbang hukuman yang dicantumkan dalam Undang-Undang Pencucian Uang, yaitu 20 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar.
Rancangan KUHP yang akan disahkan juga terlihat tidak mengikuti perkembangan zaman, dengan memperkuat vonis hukuman mati. Di banyak negara, vonis hukuman mati sudah ditiadakan karena dinilai melanggar hak asasi manusia dan tak terbukti mampu mengurangi kejahatan. Perserikatan Bangsa-Bangsa pun sudah menyatakan hukuman mati "tak lagi memiliki tempat di abad ke-21 ini". Indonesia justru memilih bertahan bersama 22 negara lain di dunia yang menerapkan hukuman mati.
Dengan bejibun masalah, sudah sepantasnya pengesahan Rancangan KUHP dibatalkan. Presiden sebaiknya memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menghentikan pembahasan dengan parlemen yang sudah masuk tahap akhir. Pembahasan Rancangan KUHP masih bisa dilakukan oleh DPR periode mendatang, dengan kajian yang lebih komprehensif, terutama pada pasal-pasal yang dianggap bermasalah dan mengancam demokrasi.
Pemerintah dan DPR tak perlu menjadikan KUHP baru sebagai warisan atau keberhasilan legislasi nasional yang tersendat-sendat selama lima tahun ini. Memaksakan pengesahan sebelum masa jabatan DPR periode ini berakhir menunjukkan bahwa pemerintah dan parlemen tak beriktikad baik dalam memperbaiki sistem hukum Indonesia.